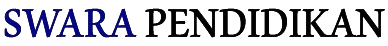Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), semula digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi modern Indonesia dan tonggak sejarah pertama di Asia Tenggara. Namun di balik euforia pencapaian teknologi ini, muncul problematika serius dalam aspek tata kelola, akuntabilitas publik, dan risiko fiskal negara.
Menurut laporan AP News (2023) dan The Australian (2024), biaya pembangunan proyek meningkat drastis dari estimasi awal hingga mencapai US$7,3 miliar atau sekitar Rp116 triliun, dengan pembiayaan utama dari China Development Bank (CDB). Sementara jumlah penumpang jauh di bawah target awal, sehingga pendapatan operasional belum mampu menutupi beban utang. Bila situasi ini dibiarkan, potensi kerugian negara baik langsung maupun melalui intervensi BUMN dan APBN bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan ancaman fiskal yang nyata.
Kegagalan Tata Kelola Proyek Publik
Kegagalan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) dapat dipahami melalui kacamata teori tata kelola publik (public governance theory) dan teori principal–agent. Dalam kerangka ini, hubungan antara pemerintah sebagai principal dan pelaksana proyek, baik BUMN maupun konsorsium seperti PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai agent, kerap diwarnai oleh asimetri informasi dan lemahnya mekanisme akuntabilitas. Pemerintah, yang seharusnya menjadi pengendali kebijakan dan penjaga kepentingan publik, sering kali tidak memiliki informasi yang sama lengkapnya dengan pihak pelaksana proyek di lapangan. Ketidakseimbangan ini menciptakan ruang bagi potensi manipulasi data, proyeksi optimistis yang tidak realistis, serta keputusan finansial yang tidak sepenuhnya berbasis pertimbangan efisiensi publik.
Thomas, P. G. (2007) dalam tulisannya yang berjudul “Why is performance-based accountability so popular in theory and difficult in practice” menegaskan bahwa tata kelola proyek publik cenderung gagal bila pengawasan berbasis kinerja (performance-based control) tidak diimbangi dengan pengawasan berbasis akuntabilitas (accountability-based control). Dalam hal KCJB, dapat dilihat bahwa pemerintah lebih menekankan pada aspek percepatan dan pencapaian simbolik proyek yakni menjadikannya sebagai ikon kemajuan teknologi nasional daripada memastikan efisiensi biaya dan transparansi dalam setiap tahap pelaksanaannya. Orientasi politik terhadap kecepatan dan pencitraan publik inilah yang kerap menyebabkan pengabaian pada aspek fundamental tata kelola, yaitu kejelasan tanggung jawab, audit keuangan yang independen, dan pengawasan kontraktual yang ketat.
Kegagalan pengendalian risiko juga dapat dijelaskan melalui teori moral hazard dalam proyek BUMN. Ketika risiko finansial suatu proyek besar sebagian besar ditanggung oleh negara atau dijamin melalui instrumen publik seperti APBN atau jaminan BUMN, para pelaksana cenderung mengambil keputusan yang lebih berisiko karena merasa terlindungi oleh “payung negara”. Dalam situasi seperti itu, akuntabilitas manajerial melemah, sementara insentif untuk bertindak hati-hati menjadi rendah. Akibatnya, pembengkakan biaya, perubahan kontrak yang tidak efisien, dan ketidaksesuaian antara rencana serta hasil menjadi hal yang nyaris sistemik.
Sehingga kegagalan dalam tata kelola proyek publik seperti KCJB bukan semata disebabkan oleh faktor teknis atau administratif, tetapi lebih mendasar, yaitu adanya ketimpangan peran dan tanggung jawab antara aktor publik dan korporasi negara, lemahnya transparansi, serta budaya pengawasan yang reaktif, bukan preventif. Tanpa reformasi menyeluruh pada sistem tata kelola yang menempatkan akuntabilitas di atas pencapaian simbolik dan proyek strategis nasional berisiko terus mengulang pola kegagalan serupa di masa depan.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Dalam tanggung jawab, tidak ada satu pihak yang dapat berdiri sendiri sebagai pelaku tunggal. Namun, jika ditelaah dengan pendekatan hukum publik dan teori governance accountability, tanggung jawab utama harus dilihat secara berlapis, mulai dari manajemen proyek, pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, lembaga pengawas, hingga struktur BUMN yang menjadi tulang punggung pembiayaan.
Secara operasional, KCIC sebagai pelaksana proyek berada di posisi paling dekat dengan keputusan teknis, kontraktual, dan finansial. Bila di kemudian hari terbukti terjadi mark-up biaya atau pelanggaran spesifikasi teknis, tanggung jawab hukum melekat pada jajaran manajemen dan kontraktor utama. Pembiayaan proyek ini melibatkan pinjaman besar dari China Development Bank dengan skema kolateral dan risiko gagal bayar (default risk) yang tinggi. Dengan struktur seperti ini, KCIC tidak hanya berperan sebagai operator, tetapi juga sebagai peminjam dengan beban finansial masif. Dalam kerangka Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), kelalaian manajemen yang menimbulkan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum bila terbukti ada unsur kelalaian berat atau penyalahgunaan kewenangan.
Sementara pemerintah, khususnya pada masa Presiden Joko Widodo yang mendorong proyek ini sebagai proyek strategis nasional memiliki tanggung jawab politik dan administratif yang tidak kalah besar. Sebagai pemilik saham mayoritas melalui konsorsium BUMN, pemerintah berada dalam posisi pengambil keputusan strategis, yaitu dari penetapan rute, pembebasan lahan, hingga penyetujuan pinjaman luar negeri. Dalam teori public accountability, keputusan investasi publik yang diambil tanpa dasar studi kelayakan ekonomi yang realistis termasuk dalam kategori mismanagement. Jika ternyata terdapat keputusan yang diambil berdasarkan proyeksi penumpang yang terlalu optimistis atau informasi finansial yang tidak akurat, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip due diligence dan bahkan bisa masuk ke ranah penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.
Kondisi ini tidak hanya unik bagi Indonesia. Flyvbjerg, B. (2014) dalam kajiannya tentang megaprojects di berbagai negara menemukan bahwa sekitar 45–60% proyek besar dunia mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) dan keterlambatan waktu akibat kombinasi antara political bias dan optimism bias. Fenomena serupa tampak pada proyek KCJB, di mana narasi kebanggaan nasional dan target ambisius cenderung menutupi perhitungan ekonomi yang realistis.
Dari sisi pengawasan, kelemahan struktural juga menjadi faktor kunci. Fungsi kontrol dari lembaga seperti KPK, BPK, dan inspektorat seharusnya berjalan sebagai sistem pengaman utama untuk memastikan setiap proses pengadaan dan pembiayaan berlangsung sesuai asas transparansi dan akuntabilitas. Namun, jika pengawasan dilakukan secara formalistik tanpa evaluasi substantif, maka yang terjadi adalah omission liability tanggung jawab karena kelalaian atau pembiaran terhadap potensi penyimpangan. Dalam konteks hukum publik, kelalaian pengawasan bukan hanya kesalahan administratif, tetapi bisa menjadi bentuk kontribusi terhadap kerugian negara.
Adapun tanggung jawab terbesar tidak dapat dilepaskan dari pemegang saham dan konsorsium BUMN yang memiliki 60% kepemilikan atas KCIC. Dalam teori state-owned enterprise governance, kegagalan proyek publik semacam ini tidak hanya mencerminkan kegagalan korporasi, tetapi juga state failure. Direksi dan komisaris BUMN wajib memastikan setiap investasi memiliki dasar ekonomi dan hukum yang kuat melalui proses due diligence dan risk assessment. Bila pengambilan keputusan dilakukan tanpa analisis memadai, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas.
Perbandingan Kasus Internasional
Kasus kereta cepat Wuhan–Guangzhou di Tiongkok pada tahun 2011 merupakan contoh klasik tentang bagaimana political interference dapat menimbulkan konsekuensi fatal. Proyek ini awalnya dipuji sebagai simbol kemajuan teknologi transportasi China, namun segera berubah menjadi skandal nasional ketika Menteri Perkeretaapian, Liu Zhijun, terjerat kasus korupsi besar-besaran. Liu terbukti menerima suap dan mengatur kontrak proyek secara tidak transparan, hingga akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan penundaan pelaksanaan. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan negara dengan kemampuan teknis tinggi sekalipun tidak kebal terhadap korupsi jika pengawasan publik dan institusi penegak hukum tidak berjalan independen. Political interference di tingkat kementerian menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih berorientasi pada ambisi politik ketimbang rasionalitas ekonomi. Dari kasus ini, Indonesia dapat belajar bahwa keberhasilan infrastruktur besar tidak dapat dilepaskan dari integritas pejabat dan sistem audit yang kuat; tanpa itu, kemajuan teknologi hanya menutupi kelemahan tata kelola.

Sumber: https://www.aman-palestine.org/en/media-center/650.html
Berbeda konteksnya, proyek California High-Speed Rail (AS) yang dimulai pada 2018 memperlihatkan sisi lain dari tata kelola yang demokratis namun kompleks. Proyek ambisius yang diharapkan menghubungkan San Francisco dan Los Angeles itu mengalami pembengkakan biaya dari perkiraan awal US$33 miliar menjadi lebih dari US$113 miliar. Audit publik yang dilakukan oleh California State Auditor menemukan bahwa estimasi awal biaya dan waktu pengerjaan terlalu optimistis, serta tidak mempertimbangkan risiko lingkungan dan hukum secara realistis. Namun, yang membedakan proyek Amerika ini dari kasus di negara berkembang adalah transparansi proses koreksi kebijakan. Ketika pembengkakan biaya tidak dapat dihindari, pemerintah negara bagian tidak menutupi kegagalan tersebut, tetapi menghentikan sebagian proyek, melakukan restrukturisasi terbuka, dan menyusun ulang jadwal serta pendanaan berdasarkan hasil audit independen. Dalam teori public management reform, praktik ini menunjukkan penerapan adaptive governance, yaitu kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi empiris, bukan tekanan politik. Bagi Indonesia, pelajaran yang dapat diambil ialah bahwa transparansi dan keterbukaan audit merupakan mekanisme paling efektif untuk memulihkan kepercayaan publik ketika proyek besar mulai menunjukkan gejala gagal finansial.
Sementara kasus Kereta Cepat Malaysia–Singapura (HSR) pada tahun 2021 menggambarkan bagaimana keputusan politik yang berani untuk membatalkan proyek justru dapat dianggap sebagai bentuk responsible governance. Proyek lintas negara yang direncanakan untuk menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura itu akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah Malaysia karena pembengkakan biaya dan ketidakpastian manfaat ekonomi. Yang menarik, pembatalan tersebut dilakukan secara terbuka setelah kajian ekonomi menunjukkan bahwa potensi keuntungan jangka panjang tidak sebanding dengan beban fiskal negara. Pemerintah Malaysia bahkan secara eksplisit mengakui bahwa perencanaan awal proyek dilakukan dengan estimasi yang “terlalu optimistis” dan kemudian menegosiasi ulang perjanjian dengan Singapura tanpa menutup-nutupi kesalahan. Keputusan ini memperlihatkan bagaimana transparency in failure, yaitu keterbukaan dalam mengakui kegagalan justru menjadi cerminan kedewasaan tata kelola publik.
Jika dibandingkan, ketiga kasus di atas menempatkan proyek KCJB dalam posisi reflektif. Indonesia berada di antara dua ekstrem, yaitu di satu sisi, ada risiko seperti di Tiongkok di mana pengawasan internal tidak cukup kuat untuk mencegah korupsi pada proyek strategis nasional, dan di sisi lain, Indonesia belum memiliki budaya transparency in failure seperti Amerika Serikat atau Malaysia, yang berani mengakui kesalahan dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil audit publik.
Diskursus Hukum dan Tanggung Jawab Pidana
Dalam perspektif hukum Indonesia, persoalan tanggung jawab pidana dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung tidak dapat dilepaskan dari perdebatan klasik antara maladministrasi, negligence, dan criminal intent. Diskursus hukum yang muncul tidak sekadar bertanya “siapa yang bersalah,” tetapi lebih mendasar, yaitu “apakah kesalahan itu bersifat pidana atau administratif?”
Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan (mens rea) menjadi kunci. Pidana hanya dapat dikenakan apabila terbukti terdapat niat jahat atau kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, tindakan seperti mark-up dalam pengadaan, kickback, atau pemalsuan dokumen kontrak merupakan bentuk penyimpangan yang jelas masuk kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Demikian pula, bila terdapat penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan proyek, misalnya pejabat publik yang menandatangani perjanjian dengan data yang tidak benar atau dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk abuse of power yang memiliki konsekuensi pidana.
Namun, hukum juga membedakan antara niat jahat dan kesalahan manajerial. Bila yang terjadi adalah kegagalan dalam perencanaan atau manajemen risiko tanpa indikasi niat untuk memperkaya diri atau pihak lain, maka penyelesaiannya seharusnya tidak melalui jalur pidana. Dalam hal ini, tanggung jawab administratif atau manajerial lebih tepat digunakan. Misalnya, pejabat atau direksi dapat dikenai sanksi berupa pencopotan jabatan, penggantian rugi, atau pembatasan kewenangan, tetapi bukan penjara. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum administrasi modern, yang menekankan bahwa setiap sanksi harus sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap kepentingan publik.
Prinsip ini juga didukung oleh Zeng, S. X., Ma, H. Y., Lin, H., Zeng, R. C., & Tam, V. W. (2015) dalam laporannya di International journal of project management yang berjudul Social responsibility of major infrastructure projects in China, yang menegaskan bahwa dalam proyek infrastruktur publik berskala besar, batas antara “kesalahan strategis” dan “penyimpangan etis” harus dibuat jelas. Fisse, B. (1982) memperingatkan bahwa kriminalisasi terhadap semua bentuk kegagalan manajerial justru dapat menimbulkan efek jera yang salah arah, dan pejabat publik akan menjadi terlalu berhati-hati, bahkan takut mengambil keputusan yang berisiko inovatif, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan.
Dalam kerangka itu, proyek KCJB harus dilihat dengan keseimbangan antara accountability dan fairness. Jika audit forensik membuktikan adanya praktik manipulasi, kolusi, atau rekayasa pembiayaan, maka langkah hukum tegas dan pidana harus diambil. Namun, jika masalah utamanya adalah optimism bias, proyeksi ekonomi yang keliru, atau lemahnya studi kelayakan tanpa unsur penipuan, maka mekanisme tanggung jawab administratif menjadi jalan yang lebih adil dan proporsional.
Apa selanjutnya dalam polemik ini?
Langkah ke depan dalam penyelesaian persoalan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung tidak boleh berhenti pada pencarian kambing hitam atau wacana politik semata. Untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah pengulangan kesalahan di masa depan, diperlukan pendekatan sistematis berbasis hukum, tata kelola, dan integritas kelembagaan.
Pertama-tama, audit forensik independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi langkah paling mendesak. Audit semacam ini tidak sekadar bertujuan untuk menghitung kerugian negara, tetapi juga memetakan rantai tanggung jawab, baik yang bersifat langsung (seperti manajemen proyek dan kontraktor) maupun tidak langsung (pejabat pemerintah, auditor internal, hingga pengambil keputusan politik). Audit forensik berbeda dari audit reguler karena menelusuri motif, kronologi keputusan, dan potensi pelanggaran hukum yang tersembunyi di balik angka-angka laporan keuangan. Dalam kasus-kasus besar internasional, seperti proyek kereta cepat di Spanyol atau Brasil, audit forensik terbukti mampu membuka praktik cost manipulation dan kolusi antara pejabat publik dan kontraktor swasta.
Kedua, transparansi data kontrak dan pinjaman wajib menjadi prinsip utama. Proyek ini menggunakan dana publik, melibatkan jaminan negara, dan berpotensi menimbulkan risiko fiskal jangka panjang. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana struktur pembiayaan disusun, siapa penerima manfaat terbesar, dan apa konsekuensinya bila terjadi gagal bayar. Dalam praktik good governance, keterbukaan dokumen kontrak dan skema pinjaman lintas negara merupakan bentuk public disclosure yang melindungi kepentingan fiskal sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Tanpa transparansi, setiap restrukturisasi utang atau pembengkakan biaya akan selalu mencurigakan, bahkan jika dilakukan dengan alasan teknis.
Ketiga, diperlukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama ini, BUMN kerap dijadikan kendaraan politik untuk mewujudkan proyek-proyek besar tanpa kajian kelayakan yang matang. Fenomena ini menunjukkan apa yang disebut oleh ekonom Joseph Stiglitz sebagai state capture, yakni ketika kebijakan publik dikendalikan oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu, bukan oleh prinsip efisiensi dan kesejahteraan publik. Reformasi tata kelola BUMN harus mengarah pada pemisahan tegas antara peran bisnis dan peran politik, dengan menegakkan kewajiban feasibility study, analisis risiko, dan audit independen sebelum proyek dijalankan.
Keempat, sebagai pembelajaran kelembagaan jangka panjang, pemerintah perlu membentuk Infrastructure Integrity Office, seperti yang diterapkan di Singapura melalui Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dan Infrastructure Integrity System. Lembaga ini berfungsi untuk mengawasi risiko korupsi dan konflik kepentingan sejak tahap perencanaan proyek, bukan setelah terjadi penyimpangan. Di Singapura, setiap proyek strategis wajib melalui integrity screening sebelum ditetapkan, memastikan bahwa proses perancangan, pengadaan, dan kontrak bebas dari intervensi politik dan manipulasi biaya.
Sehingga empat langkah tersebut, Indonesia dapat bergerak dari sekadar damage control menuju reformasi tata kelola yang substantif. Proyek kereta cepat ini seharusnya menjadi pelajaran nasional tentang pentingnya checks and balances antara ambisi pembangunan dan tanggung jawab fiskal. Audit forensik yang transparan, tata kelola BUMN yang profesional, dan lembaga integritas infrastruktur yang kuat akan menjadi fondasi agar proyek-proyek besar di masa depan benar-benar membawa kemajuan, bukan beban bagi generasi berikutnya.
Referensi
Arief, M Irsan. Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana (Korupsi). MCL Publisher, 2022.
Brunner, Ronald D. “Adaptive governance as a reform strategy.” Policy sciences 43, no. 4 (2010): 301–41.
Chen, Xueming. “A sustainability analysis on the Wuhan-Guangzhou high-speed railway in China.” International Journal of Sustainable Transportation 9, no. 5 (2015): 348–63.
Clarkson, Christopher MV. Understanding criminal law. Sweet & Maxwell, 2005.
Eakin, Hallie, Siri Eriksen, Per-Ove Eikeland, dan Cecilie Øyen. “Public sector reform and governance for adaptation: implications of new public management for adaptive capacity in Mexico and Norway.” Environmental management 47, no. 3 (2011): 338–51.
Fisse, Brent. “Reconstructing corporate criminal law: Deterrence, retribution, fault, and sanctions.” S. Cal. L. Rev. 56 (1982): 1141.
Flyvbjerg, Bent. “What you should know about megaprojects and why: An overview.” Project management journal 45, no. 2 (2014): 6–19.
Gailmard, Sean. “Accountability and principal-agent theory.” The Oxford handbook of public accountability, Oxford University Press Oxford, 2014, 90–105.
Jermias, Johnny, Yuanlue Fu, Chenxi Fu, dan Yasheng Chen. “Budgetary control and risk management institutionalization: a field study of three state-owned enterprises in China.” Journal of Accounting & Organizational Change 19, no. 1 (2023): 63–88.
Katsamunska, Polya. “The concept of governance and public governance theories.” Economic alternatives 2, no. 2 (2016): 133–41.
Kusworo, Daffa Ladro, dan Titi Anggraini. “Extensive interpretation of state financial losses in tin sector corruption: A comparative study of emerging economies.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 10, no. 2 (2024): 173–86.
Mwaura, Kiarie. “The failure of corporate governance in state owned enterprises and the need for restructured governance in fully and partially privatized enterprises: The case of Kenya.” Fordham Int’l LJ 31 (2007): 34.
Parchomiuk, Jerzy. “Abuse of discretionary powers in Administrative Law. Evolution of the judicial review models: from ‘administrative morality’ to the principle of proportionality.” Časopis pro právní vědu a praxi 26, no. 3 (2018): 453–78.
Peterman, David Randall. The high-speed intercity passenger rail (HSIPR) grant program: overview. Congressional Research Service, 2016.
Prasetio, Lilik. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia.” The Prosecutor Law Review 2, no. 3 (2024).
Qian, Wendy. Comparative Case Studies of Rent-Seeking in China’s State-Owned Enterprises: the Ministry of Railway and China Mobile. 2012.
Rajaram, Anand, Tuan Minh Le, Nataliya Biletska, dan Jim Brumby. “A diagnostic framework for assessing public investment management.” World Bank policy research working paper, no. 5397 (2010).
Sani, Tantra Perdana, Alvi Syahrin, dan Mahmud Mulyadi. “Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengerjaan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan yang Menimbulkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN Medan Nomor 38/PID. SUS-TPK/2022/PN MDN).” UNES Law Review 6, no. 4 (2024): 11896–906.
Thomas, Paul G. “Why is performance-based accountability so popular in theory and difficult in practice.” World Summit on Public Governance: Improving the Performance of the Public Sector. Taipei, 2007, 1–3.
Wu, Yuan. Risk management and risk control for state-owned firms of China. University of Reading, 2019.
Zahariadis, Nikolaos. Ambiguity and choice in public policy: Political decision making in modern democracies. Georgetown university press, 2003.
Zeng, SX, HY Ma, He Lin, RC Zeng, dan Vivian WY Tam. “Social responsibility of major infrastructure projects in China.” International journal of project management 33, no. 3 (2015): 537–48.
Profil Penulis
Ruben Cornelius Siagian adalah peneliti, penulis opini, dan jurnalis yang sering menulis tentang isu-isu sains, politik, dan geopolitik, terutama terkait dinamika internasional dan kebijakan publik di Indonesia.